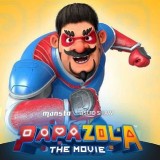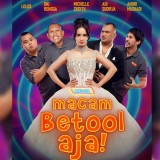TIMES SLEMAN, SLEMAN – Meledeknya kecemasan akan kehilangan ruang hidup dan batas kedaulatan, perhatian publik terbelah antara kegelisahan ekologis dan kegaduhan politik nasional. Raja Ampat, yang selama ini dielu-elukan sebagai surga biodiversitas laut, bergeser citranya menjadi simbol ketimpangan antara eksploitasi dan pelestarian.
Kemarahan merebak, media sosial berubah menjadi arena wacana, tempat kemarahan dan harapan saling menyalip, dan tempat opini dibentuk secepat algoritma merekam emosi. Isu lingkungan bukan lagi milik aktivis atau akademisi, tetapi telah menjadi milik publik.
Tagar #SaveRajaAmpat yang sempat digunakan lebih dari 300 ribu kali pada awal Juni 2025, membanjiri sosial media dan ketika video kerusakan laut yang dirilis oleh greenpeace.id di Instagram mencapai lebih dari 13 juta penayangan dalam hitungan hari.
Sementara di ujung barat, 4 pulau menjadi sengketa antara dua provinsi membuka babak baru persoalan batas administratif dan nasionalisme lokal. Di media, sengketa ini dibingkai dalam spektrum sempit antara siapa yang berhak dan siapa yang akan menang.
Tetapi jauh dari itu, narasi yang berkembang menunjukkan bahwa masalah ini telah dimediasi, dikemas, dan disulap menjadi konsumsi publik yang menegangkan. Konflik administratif berubah menjadi drama geopolitik lokal yang menarik simpati dan perhatian nasional.
Kepungan isu yang menghangatkan ruang publik ini menjadi semacam panggung besar yang dengan sendirinya menanti sosok penyelamat untuk tampil di tengah sorotan. Topik ini terlalu menggoda untuk tidak dieksplorasi oleh media.
Ia penuh konflik, emosi, lanskap indah yang dirusak, dan keresahan yang bisa dijahit menjadi cerita nasionalisme, dan seperti setiap drama besar dalam narasi kebangsaan panggung itu pun butuh figur sentral.
Seseorang yang bisa hadir tidak hanya sebagai pejabat, tapi sebagai lambang ketegasan, pemilik solusi, dan wajah dari penyelamat.
Mediatisasi Kepahlawanan dari Pemberitaan ke Imaji Simbolik
Dalam politik modern, tokoh publik tidak lagi hanya dinilai dari apa yang dilakukan, tetapi dari bagaimana ia ditampilkan. Di sinilah konsep mediatisasi kepahlawanan berperan.
Dalam konteks ini, Prabowo bukan hanya muncul sebagai pejabat negara yang menjalankan tugas administratif. Ia tampil sebagai figur simbolik yang diposisikan oleh media sebagai representasi ideal dari tindakan tegas dan patriotik.
Di tengah kemarahan publik terhadap eksploitasi Raja Ampat, media menghadirkan narasi bahwa Prabowo lah yang menghentikan tambang, dan yang mengambil langkah cepat demi kedaulatan lingkungan.
Realitas birokratis yang sebenarnya kompleks melibatkan Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah diredam dan disimplifikasi menjadi satu wajah tunggal yang mewakili negara. Transformasi ini bukan netral, ia terjadi karena kebutuhan akan figur penyelamat, karakter yang mudah diidentifikasi oleh publik, emosional, dan kuat.
Media massa dan media sosial bekerja secara simultan dalam membentuk narasi ini, tidak hanya melalui berita, tetapi juga melalui gambar, cuplikan video, dan kutipan yang dipotong untuk mengedepankan peran tunggal sang presiden.
Dalam banyak pemberitaan, sosok Prabowo seolah hadir sebagai pemutus segala keraguan, padahal dalam kenyataan administratif, keputusan pencabutan izin adalah hasil mekanisme hukum, protes warga, dan tekanan aktivisme sipil yang sedang berlangsung. Tetapi seperti yang diungkap oleh John B.
Thompson (2005) dalam kajian mediated visibility, politik masa kini adalah soal “siapa yang tampak” bukan “siapa yang bertindak”. Maka dari itu, ketampakan Prabowo dalam narasi media menjadi lebih penting daripada rekam fakta detailnya.
Narasi ini bekerja melalui emosi kolektif dan kelelahan publik terhadap birokrasi. Masyarakat Indonesia, yang telah lama terpapar kompleksitas aturan, konflik antar instansi, dan lambannya tindakan negara dalam isu lingkungan, cenderung mencari solusi personalistik.
Maka ketika media menyuguhkan figur tunggal yang berani mengambil sikap, responsnya adalah rasa lega, bahkan kekaguman. Dalam sosiologi media, ini disebut sebagai affective framing, strategi pemberitaan yang menggugah emosi dengan menyisipkan peran-peran heroik dalam krisis yang sebenarnya multidimensional.
Simbol dan Selektivitas Apa yang Disembunyikan
Dalam lanskap pemberitaan tentang sengketa 4 pulau, selektivitas juga menjadi kunci produksi makna. Media memilih untuk menonjolkan aspek-aspek dramatis seperti kemarahan warga, klaim sepihak, pernyataan bernada nasionalisme, sementara mengaburkan akar persoalan.
Ketidakakuratan data, lemahnya komunikasi lintas pemerintahan, dan absennya transparansi dalam tata kelola wilayah yang terlihat adalah emosi, bukan struktur, lalu yang muncul adalah simbol, bukan proses. Seperti yang dijelaskan oleh Stuart Hall (1980) dalam konsep preferred meaning, media tidak hanya menyampaikan realitas, tetapi memberikan arah tafsir terhadap realitas tersebut.
Wacana tentang siapa yang bersalah menjadi lebih penting ketimbang bagaimana sistem administrasi bekerja atau gagal. Maka, kemarahan bukan lagi diarahkan pada sistem, tetapi pada figur dan lebih jauh lagi, pada kebutuhan akan figur lain yang bisa hadir memberi solusi.
Di sinilah kebutuhan akan figur sentral masuk ke dalam framing media. Dalam banyak pemberitaan, Prabowo Subianto kembali disisipkan sebagai aktor yang “memantau”, “menegaskan pentingnya keutuhan wilayah”, atau “siap bertindak jika dibutuhkan”.
Padahal, wewenang langsung dalam penyelesaian konflik ini ada pada Kemendagri dan kedua kepala daerah. Namun wajah dan nama Prabowo ditampilkan bukan karena fungsinya dalam sistem, melainkan karena nilai simboliknya dalam menjawab keresahan publik.
Dalam situasi ini, realitas dikonstruksi secara strategis. Apa yang terlihat bukanlah cerminan utuh dari apa yang terjadi, melainkan versi yang telah disusun agar publik merasa perlu percaya, marah, lalu tenang kembali setelah kehadiran simbolik seorang penyelamat diberitakan.
Akhirnya, konflik administratif berubah menjadi drama identitas, dan media menjadi sutradara narasi yang memilih siapa yang patut tampil dan siapa yang ditinggalkan dalam bayang-bayang.
Raja Ampat bukan lagi hanya tentang lingkungan, dan empat pulau Aceh bukan lagi hanya soal batas wilayah. Keduanya telah menjadi latar simbolik bagi konstruksi kepahlawanan, yang disusun dengan cantik dan disebarkan oleh media massa.
Ini bukan sekadar soal siapa yang bertindak, tapi siapa yang tampak bertindak, dan dalam arena publik yang dibentuk oleh media yang tampak adalah yang dianggap nyata. Prabowo, dalam narasi ini, tak sekadar pejabat tinggi negara.
Ia diposisikan sebagai mitos yang berjalan, pahlawan di tengah ancaman tambang, penjaga kedaulatan di batas wilayah. Bukan karena seluruh proses berada di tangannya, tetapi karena media memilih untuk menaruh sorot pada wajahnya, pada suaranya, dan pada gesturnya, lalu membungkus semuanya dalam kisah penyelamatan.
***
*) Oleh : Aditya Febriyan, Mahasiswa Pascasarja FIsipol UGM dan Produser Musik.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |